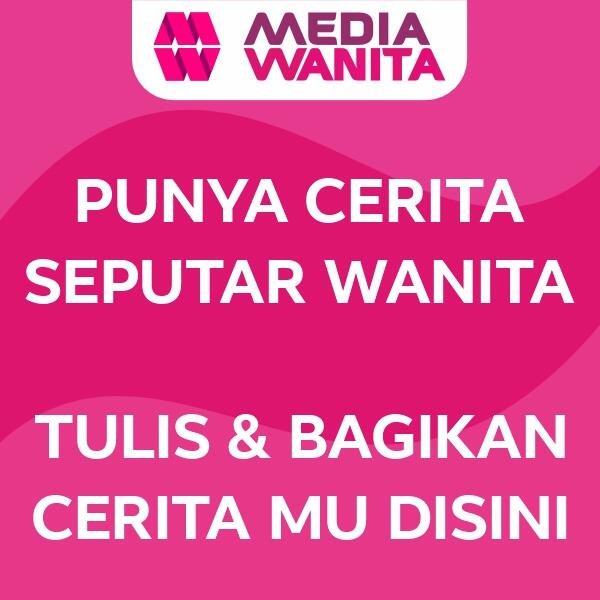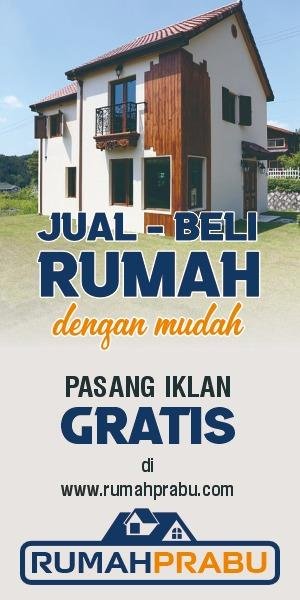Fintech telah mengubah cara kita berhubungan dengan uang. Aplikasi pembayaran, dompet digital, dan platform pinjaman kini menjadi bagian dari rutinitas harian. Namun perubahan terbesar sesungguhnya bukan terjadi pada teknologi, melainkan pada perilaku manusia saat berhadapan dengan uang yang tak lagi berbentuk fisik. Di sinilah perilaku keuangan (behavioral finance) menunjukkan betapa emosi dan impuls sering lebih dominan daripada logika.
Fenomena yang kini sedang viral—mulai dari “paylater untuk gaya hidup”, tagihan menumpuk karena FOMO belanja 11.11 dan 12.12, sampai kasus anak muda yang terjebak pinjol karena kebutuhan konsumtif—menunjukkan bagaimana teknologi mempercepat keputusan keuangan yang sesaat. Di aplikasi, satu gesekan layar terasa tidak berarti, padahal itu adalah keputusan finansial yang sesungguhnya. Ketika diskon berkedip dan notifikasi cashback muncul, bias kognitif seperti present bias dan overconfidence bekerja tanpa kita sadari.
Fintech memang menawarkan kecepatan, tetapi kecepatan inilah yang menjadi ujian mentalitas keuangan kita. Banyak orang merasa berani meminjam karena prosesnya mudah. Banyak pula yang merasa lebih “kaya” karena saldo e-wallet terlihat penuh, padahal itu hanya uang yang diparkir sementara. Dalam behavioral finance, ini dikenal sebagai money illusion—ketika tampilan digital membuat kita lupa bahwa uang tetaplah uang, meski bentuknya berubah.
Di sisi lain, fintech juga membawa manfaat besar. Usaha mikro mendapat akses pembiayaan dengan lebih cepat. Anak muda bisa mulai berinvestasi tanpa modal besar. Fitur-fitur seperti pencatatan transaksi otomatis memberi gambaran kesehatan keuangan yang dulu sulit dilakukan secara manual. Namun semua manfaat itu berubah menjadi risiko ketika tidak dibarengi kemampuan mengontrol diri. Aplikasi investasi yang tampilannya “ramah dan lucu” sering membuat investor pemula meneken tombol beli hanya karena melihat grafik hijau—sebuah bias herding yang sudah banyak memakan korban, terutama ketika saham atau aset digital sedang viral.
Fenomena konten “flexing finansial” di media sosial juga tak kalah memengaruhi. Banyak orang membeli barang mahal atau mengambil paylater demi citra, bukan kebutuhan. Kehidupan orang lain yang tampak mewah mendorong rasa iri, yang dalam teori perilaku keuangan disebut relative deprivation: merasa kurang hanya karena membandingkan diri dengan orang lain. Padahal, banyak dari “kemewahan” itu belum tentu dibayar tunai. Bahkan tak jarang merupakan hasil utang.
Namun fintech bukan musuh. Masalah utama justru ada pada bagaimana kita mengelola diri ketika teknologi membuat segalanya terasa instan. Solusinya bukan menjauhi aplikasi, melainkan membekali diri dengan manajemen keuangan yang lebih matang. Ada beberapa langkah yang dapat menyeimbangkan antara teknologi dan kedisiplinan.
Pertama, tetapkan anggaran khusus untuk transaksi digital. Pisahkan dana kebutuhan pokok, tabungan, dan “uang main” yang boleh dipakai untuk belanja impulsif. Ini mengurangi risiko kebablasan ketika diskon atau promo muncul.
Kedua, aktifkan fitur pengingat tagihan dan batasi limit paylater atau kartu kredit digital. Kendali batas jauh lebih efektif daripada niat semata.
Ketiga, tanamkan prinsip jeda 24 jam sebelum membeli barang yang tidak mendesak. Waktu jeda terbukti mampu meredam keputusan impulsif yang dipicu FOMO belanja.
Keempat, edukasi diri sebelum berinvestasi. Selalu mulai dari produk berisiko rendah, pahami profil risiko pribadi, dan hindari keputusan hanya karena melihat sesuatu sedang viral di TikTok atau X.
Fintech telah memudahkan hidup, tetapi hanya literasi dan disiplin yang bisa menyelamatkan kita dari jebakan inovasi itu sendiri. Di era di mana dompet berpindah ke genggaman, kebiasaan keuangan yang sehat tetap harus bertumpu pada hal-hal sederhana: mengatur, menahan diri, dan berpikir sebelum menekan tombol “beli sekarang”. Dengan fondasi manajemen keuangan yang kuat, fintech bukan lagi ancaman, tetapi menjadi alat yang benar-benar membantu masa depan finansial kita.