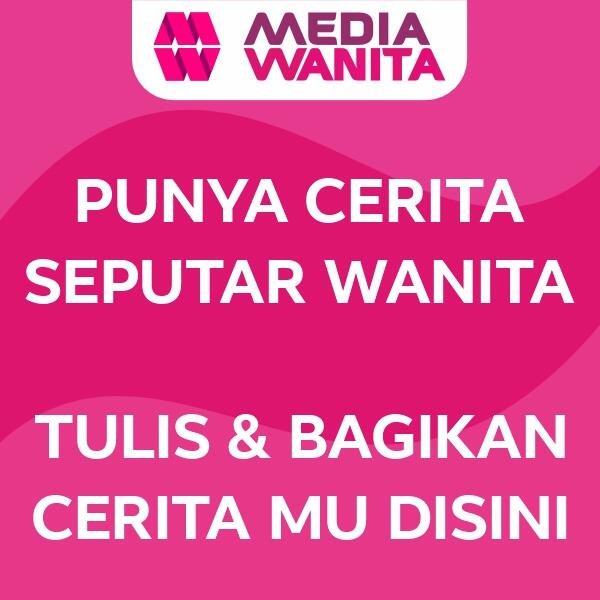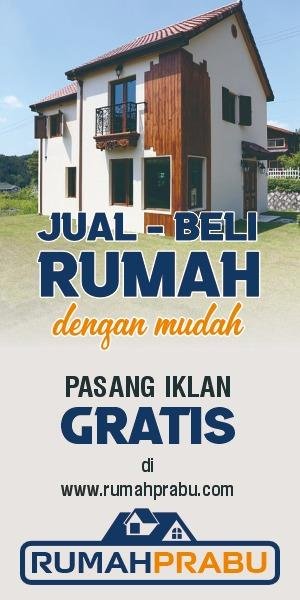Pelataran ID, Jakarta, (25/10/2025) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto lahir dengan misi mulia: memastikan setiap anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang layak tanpa terkendala kemampuan ekonomi. Di tengah gempita janji menuju Indonesia Emas 2045, MBG disebut sebagai investasi besar negara untuk membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.
Namun, seperti banyak kebijakan ambisius lain, program ini masih dihadapkan pada pertanyaan klasik: apakah niat besar itu diikuti kesiapan yang besar pula?
Menurut pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansah, MBG adalah bentuk keberpihakan nyata negara terhadap keadilan sosial, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. “Negara hadir bukan sekadar dengan bantuan tunai, tapi dengan gizi itu level keberpihakan yang lebih tinggi,” jelasnya.
Namun, ia juga menekankan bahwa keberpihakan tanpa tata kelola hanya akan menghasilkan ketimpangan baru: anak-anak mungkin kenyang, tapi belum tentu bergizi.
Konsep MBG sebenarnya sejalan dengan kebijakan di beberapa negara maju seperti Brasil, Jepang, Korea Selatan, dan Finlandia, yang menjadikan penyediaan makanan bergizi sebagai bagian integral dari sistem pendidikan. Bahkan, hubungan bilateral dengan Brasil menguat setelah Presiden mereka berkunjung ke Indonesia untuk mempelajari sistem dapur MBG sebagai referensi kebijakan pangan.
Sayangnya, di dalam negeri, sejumlah catatan kritis masih membayangi dari persoalan logistik, standar kualitas makanan, hingga kesiapan lembaga pelaksana.
Badan Gizi Nasional (BGN), yang baru dibentuk untuk menjadi motor utama pelaksanaan MBG, menghadapi tantangan berat sejak hari pertama. Lembaga ini harus memastikan ratusan dapur di seluruh daerah beroperasi sesuai standar gizi dan higienitas sebuah pekerjaan besar untuk institusi yang masih dalam tahap konsolidasi.
Pemahaman masyarakat terhadap struktur, mekanisme kerja, dan koordinasi antarinstansi BGN juga belum merata. Edukasi publik masih menjadi pekerjaan rumah besar. Tanpa edukasi yang kuat, kepercayaan publik akan mudah goyah, terutama ketika muncul kabar makanan yang basi, kemasan rusak, atau distribusi terlambat.
Sebagaimana dikatakan Trubus, “transparansi bukan hanya soal laporan keuangan, tapi soal bagaimana rakyat memahami apa yang mereka makan dan siapa yang bertanggung jawab di baliknya.”
Pelaksanaan MBG sangat bergantung pada Pemerintah Daerah (Pemda). Mereka yang paling memahami medan dan masyarakat dari akses jalan, karakter sosial-ekonomi, hingga tantangan distribusi di wilayah terpencil. Namun, di beberapa daerah, peran Pemda masih sebatas administratif: mengirim laporan, menandatangani dokumen, lalu menunggu instruksi pusat.
Padahal, fungsi pengawasan dan pembinaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seharusnya menjadi jantung program. Dari proses pengemasan hingga pengantaran, Pemda punya peran strategis untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga. “Kalau nasi tiba dalam kondisi dingin atau lauknya basi, itu bukan sekadar masalah teknis, tapi kegagalan koordinasi,” ujar Trubus memberi catatan.
Hal yang paling krusial dalam program MBG adalah menjaga kualitas dan keamanan makanan. Di sejumlah daerah, muncul laporan tentang menu yang kurang higienis atau disimpan terlalu lama sebelum dibagikan. Di sinilah pentingnya melibatkan ahli gizi di setiap dapur agar menu yang disajikan sesuai kebutuhan anak-anak, bukan sekadar memenuhi target produksi.
Idealnya, setiap dapur hanya melayani maksimal 2.000 porsi per hari agar kualitas terjaga, sementara pelatihan berkala bagi juru masak menjadi keharusan, bukan pilihan.
Pemerintah juga diharapkan lebih tegas dalam penegakan standar. Dapur yang tidak memenuhi kriteria higienis dan keamanan pangan semestinya ditutup sementara hingga memenuhi standar. Sebab dalam konteks program sebesar MBG, kesalahan kecil bisa berdampak besar: satu dapur lalai, seribu anak bisa sakit.
Partisipasi publik menjadi elemen penting keberhasilan MBG. Kepala sekolah, guru, dan komite sekolah seharusnya turut melakukan pengecekan harian terhadap makanan yang dibagikan.
Masyarakat juga dapat dilibatkan dalam proses produksi dan distribusi agar timbul rasa memiliki serta transparansi yang nyata, bukan formalitas. “Kalau publik ikut mengawasi, program ini tidak hanya berjalan, tapi dipercaya,” ungkap Trubus.
Selain itu, proses sertifikasi Kelayakan Higienis, Legal, dan Standar (KHLS) serta sertifikasi halal perlu dipermudah. Banyak dapur di tingkat lokal menghadapi kesulitan biaya dalam mengurus sertifikasi, padahal mereka beroperasi dengan niat tulus untuk melayani anak-anak. Di titik ini, kebijakan seharusnya hadir bukan untuk mempersulit, melainkan memampukan.
Dengan target 82 juta penerima manfaat, MBG membutuhkan sistem digital yang kuat dan transparan.
Pemantauan berbasis data real-time akan membantu memastikan kualitas makanan, mencegah keterlambatan distribusi, serta meminimalisir penyimpangan. Namun, digitalisasi tak akan berarti jika birokrasi masih berpikir manual. Data hanya akan menjadi angka tanpa makna jika tidak diikuti disiplin dan integritas di lapangan.
Program MBG sejatinya adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang kuat bukan sekadar program populis yang menggugah headline. Namun, seperti diingatkan banyak pengamat, keberhasilan program ini tidak ditentukan oleh jumlah porsi yang dibagikan, melainkan oleh konsistensi, kejujuran, dan integritas dalam pelaksanaan.
Di sinilah ujian sebenarnya: apakah negara benar-benar sedang memberi gizi untuk rakyatnya, atau sekadar memberi makan agar terlihat peduli?